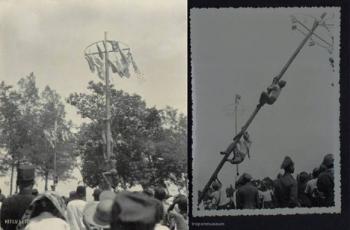PANCASILA - walaupun tak cukup disebut sebagai doktrin, tetapi hampir mirip dengan doktrin- merupakan himbauan normatif yang dijadikan sebagai ideologi negara. Sebagai ideologi, Pancasila mengandung kumpulan ide, prinsip, mitologi, atau simbol untuk mengarahkan kepada tujuan yang jika ditelusuri sejarahnya adalah untuk mengkonstruksi Indonesia sebagai sebuah negara- nasional (nation-state). Hanya saja, yang perlu diperhatikan adalah bahwa konstruksi negara-bangsa Indonesia berkarakter cukup unik. Ia tidak berwatak sekuler sebagaimana banyak negara-bangsa di Barat, tempat gagasan tentang negara-bangsa lahir.
Konsep negara-bangsa awalnya berkembang dari sistem religiopolitik- integralisme-Katholik di abad pertengahan. Sistem religiopolitik ini kemudian ditumbangkan oleh gerakan reformasi renaissance. Namun, negara-bangsa Indonesia dengan landasan dan falsafah Pancasila, bukan negara sekuler. Indonesia adalah negara modern yang berkarakter dasar religius, menjunjung tinggi nilai-nilai moral yang bersumber dari agama.
Sebagai ideologi negara, Pancasila memberikan perspektif tentang masyarakat bangsa yang dicita-citakan yang bisa menaungi seluruh kebhinnekaan yang menjadi kekayaan Indonesia. Pancasila bak sebuah tenda bangsa yang lebar, yang bisa menjadi wadah perbedaan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Pancasila bahkan bisa menjadi mediator proses negosiasi terus menerus dalam sebuah bangsa yang tak pernah tunggal dan bisa dipastikan tak akan pernah "eka". Pancasila oleh para intelektual posmodernisme Islam sering disebut sebagai titik temu di antara sekian banyak perbedaan, yang bisa melahirkan efek energi sentripetal sekaligus mencegah efek energi sentrifugal.
Selain itu, Pancasila juga merupakan panduan dalam hidup berbangsa dan bernegara yang menyeimbangkan antara manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial (zoon politicon). Keseimbangan sebagai makhluk individu dan makhluk sosial tersebut akan membuat tidak ada individu lain merasa dirugikan. Arahnya adalah tuntunan kepada setiap orang agar dalam memaksimalkan kepentingannya sendiri tetap mempunyai pertimbangan lain yang merupakan konsekuensi sebagai anggota masyarakat.
Namun, kenyataannya masih sering terjadi konflik dalam masyarakat yang disebabkan oleh perbedaan- perbedaan yang bernuansa SARA. Bahkan konflik-konflik yang terjadi seringkali mengancam eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Egoisme etnis, keagamaan, dan bahkan egoisme keberagamaan sering menampakkan wujudnya sampai melupakan cita-cita berbangsa dan bernegara. Praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) masih merajalela. Praktik ini jelas menunjukkan ekstrimisme kepentingan individual dan pengabaian terhadap hak orang lain dan bahkan menyebabkan mereka miskin.
Lebih parah lagi, Pancasila digunakan sebagai alat legitimasi untuk melakukan praktik penyelewengan-penyelewengan kekuasaan. Pancasila yang sesungguhnya mengajarkan dan menganjurkan kebaikan, tetapi justru digunakan sebagai alat untuk melangsungkan kejahatan. Realitas dan praktik itulah yang membuat Pancasila kemudian menjadi ternoda. Akibatnya, Pancasila kemudian mengalami demoralisasi dan kehilangan roh atau fungsi sebagai sumber nilai dan acuan moral bangsa. Bahkan orang kemudian tak bisa lagi membedakan antara Pancasila dengan kejahatan, karena Pancasila identik dengan praktik kejahatan. Pancasila oleh sebagian orang lalu digugat dan dianggap tidak diperlukan lagi, bahkan harus dibuang jauh-jauh.
Pancasila menjadi ternoda karena ia diinterpretasikan secara subjektif untuk kepentingan-kepentingan tertentu, dan celakanya lagi dilakukan upaya sistematis untuk memutlakkan interpretasi itu. Sesungguhnya praktik penodaan seperti ini tak ubahnya dengan teks-teks keagamaan yang sesungguhnya bernilai "sakral dan suci", penganjur kebaikan, dan pendorong perdamaian. Tetapi oleh sebagian orang, teks-teks tersebut dinterpretasikan untuk kepentingan- kepentingan sosial-politik sempit dan jangka pendek, melakukan kejahatan, menghalalkan peperangan, bahkan perang tersebut dianggap sebagai perang suci demi Tuhan (the holy war). Jadi sesungguhnya letak persoalannya bukanlah pada Pancasilanya, tetapi pada interpretator yang memaksakan interpretasinya.
Dalam Pancasila sesungguhnya terdapat prinsip untuk tidak memutlakkan yang merupakan pesan terdalam dari sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa. Logikanya adalah bahwa yang mutlak, sebagai derivasi dari sifat keesaan, hanyalah Tuhan, sedangkan yang selain-Nya adalah relatif belaka. Karena itu, menjadikan pengertian yang merupakan interpretasi dari Pancasila sebagai acuan kebenaran, sesungguhnya sama dengan menjadikan Pancasila sebagai alat teror yang secara mendasar bertentangan dengan ajaran dan semangat moral Pancasila itu sendiri.
Untuk menghindari pemutlakan terhadap sebuah interpretasi, yang mutlak harus dilakukan adalah mengikhtiarkan dialog yang disertai dengan prinsip keterbukaan untuk menemukan interpretasi baru sesuai dengan konteks dan dinamika sejarah. Yang diperlukan adalah kemampuan untuk mengoreksi kesalahan interpretasi yang telah terjadi dan memberikan interpretasi baru yang dihasilkan dari proses dialog yang bebas dari intimidasi dan hegemoni.
Jika Pancasila diinterpretasikan dalam suasana yang diliputi intimidasi dan hegemoni, maka Pancasila akan tampil sebagai media teror. Orang dicap anti-Pancasila, padahal sesungguhnya yang mencap anti-Pancasila itulah yang anti- Pancasila. Inilah yang terjadi pada Pancasila pada sebagai besar masa Orde Baru.
Dengan selalu melakukan reinterpretasi, Pancasila akan senantiasa segar dan dapat dijadikan sebagai acuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila akan terasa baru lahir kembali dan mempunyai daya dorong psikologis kuat (psychological stricking force) bagi seluruh masyarakat warga negara Indonesia untuk melaksanakannya.
Jika mau jujur, Pancasila sebagai falsafah ideologi dan dasar negara saat ini sesungguhnya semakin kokoh. Pancasila, secara konseptual, sudah semakin mendapat pengakuan sebagai titik temu dari setiap kebhinnekaan yang menjadi kekayaan Bangsa Indonesia. Sebagai salah satu contoh, dalam konteks politik, telah terjadi perubahan pandangan di kalangan umat Islam (baca: aktivis- aktivis politik Islam) yang awalnya menentang keras Pancasila sebagai dasar negara. Umat Islam tak lagi mempertentangkan Pancasila dengan Islam, tetapi justru secara kreatif terus berusaha mencari kompatibilitas atau persesuaian antara Pancasila dengan ajaran Islam. Pancasila tak lagi dianggap sebagai sebuah ideologi sekuler, tetapi dianggap mengandung nilai-nilai religius dan prinsip-prinsip lain yang terkandung dalam ajaran Islam.
Karena itu, yang terpenting sesungguhnya adalah menjalankan Pancasila secara jujur dan konsekuen dalam arti yang sebenar-benarnya. Yang sering terjadi adalah orang mempunyai pengetahuan yang cukup tentang kebaikan, tetapi kebaikan tersebut tidak dijalankan, atau bahkan melakukan yang sebaliknya.
Akhirnya, Pancasila hendaknya tak hanya dijadikan sebagai aksesori apalagi diselewengkan, melainkan benar-benar digunakan sebagai acuan tingkah laku setiap warga negara- banga Indonesia dalam kehidupan keseharian. Sebuah nilai hanya akan menjadi hidup apabila ia telah teraplikasi dan terimplementasi dalam konteks nyata, sebagaimana agama menyatakan bahwa iman tanpa amal saleh, sesungguhnya sama dengan tidak beriman sama sekali. Sebab, iman dan amal saleh ibarat dua sisi dari sekeping mata uang yang jika salah satu dari kedua sisi tersebut tidak ada, maka sama dengan ketiadaan keduanya. Wallahu a"lam bi al-shawab.
By. DETRIANDI